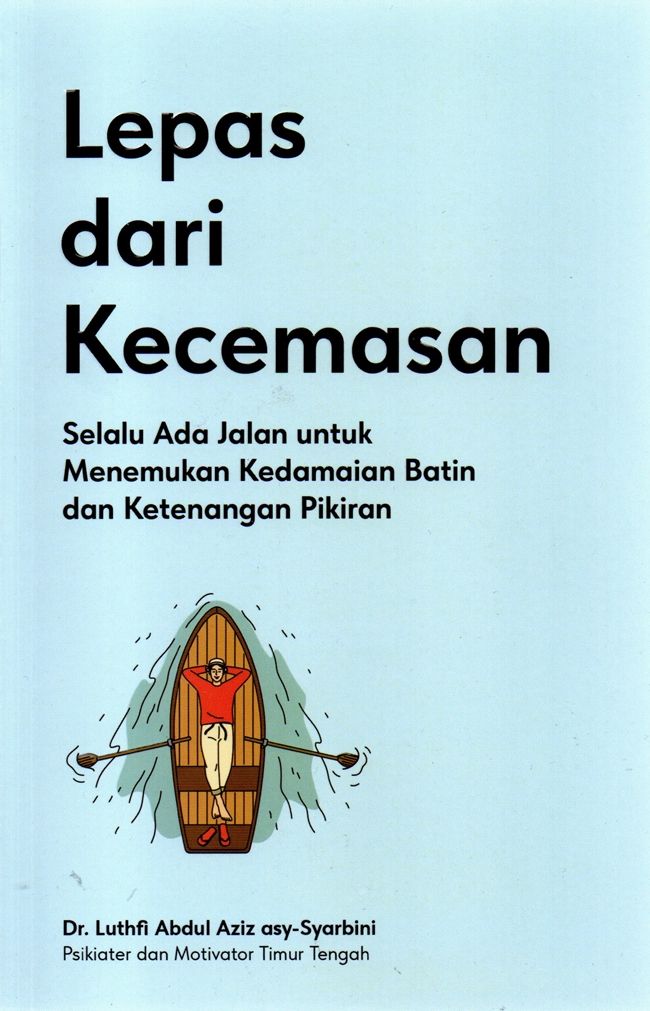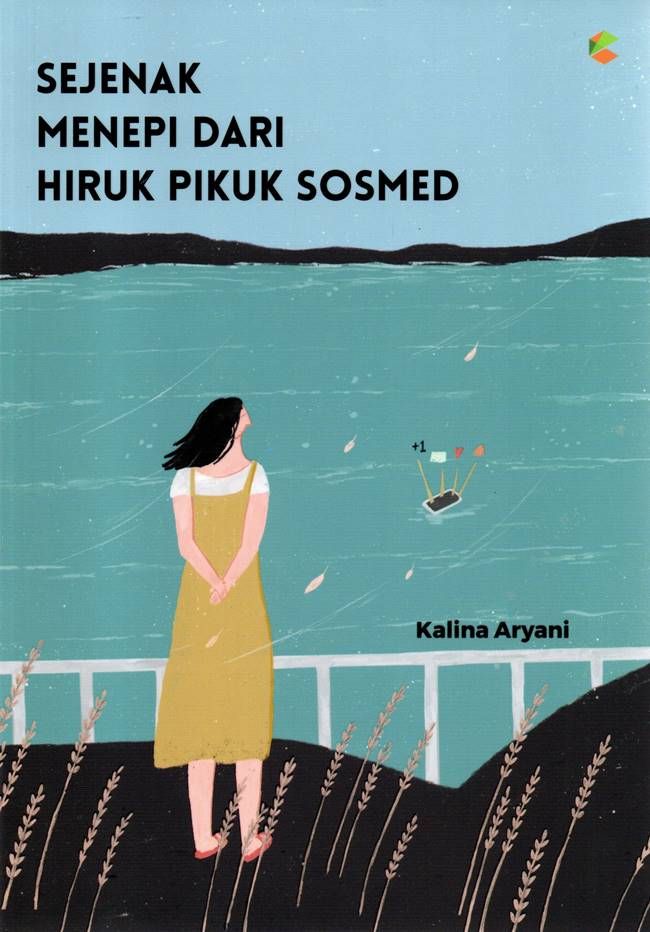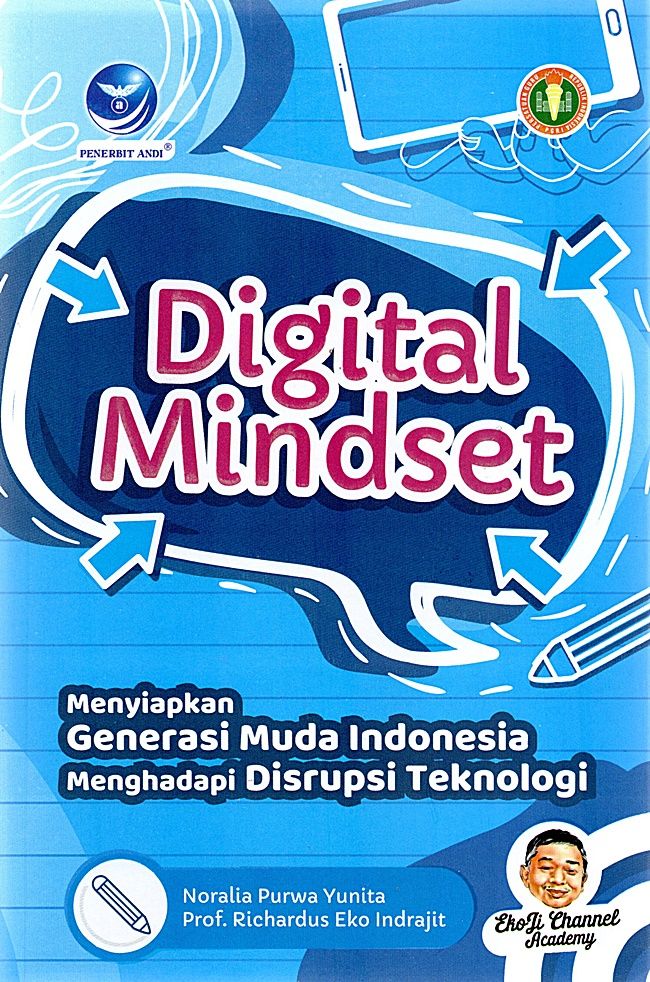fomo – Apakah Grameds pernah merasa gelisah saat melihat teman liburan ke luar negeri, beli gadget baru, atau menghadiri acara seru yang kamu lewatkan?
Nah, perasaan seperti itu disebut FOMO (Fear of Missing Out), rasa takut tertinggal dari kesenangan, tren, atau kesempatan yang sedang dinikmati orang lain.
Di era media sosial yang serba cepat, FOMO jadi hal yang sangat umum dialami banyak orang, terutama generasi muda. Padahal, kalau tidak dikendalikan, FOMO bisa membuat hidup terasa lelah dan kehilangan makna.
Yuk, kita bahas apa itu FOMO, mengapa bisa muncul, dan bagaimana cara mengatasinya agar hidupmu lebih tenang dan seimbang.
Daftar Isi
Pengertian FOMO (Fear of Missing Out)

Sumber: Pexels
FOMO atau Fear of Missing Out adalah perasaan cemas karena takut tertinggal dari pengalaman, informasi, atau kesempatan yang sedang dinikmati orang lain. Istilah ini pertama kali populer di awal tahun 2000-an ketika media sosial mulai tumbuh pesat.
Sederhananya, FOMO muncul saat kamu melihat teman liburan ke luar negeri, beli barang baru, atau dapat promosi, lalu merasa hidupmu kurang menarik dibanding mereka. Fenomena ini makin kuat di era digital, karena setiap hari kita disuguhi kehidupan “sempurna” orang lain di layar smartphone.
FOMO bukan cuma soal iri, tapi juga soal tekanan sosial; baik rasa takut kalau tidak ikut tren, tidak tahu berita terbaru, atau dianggap tidak update.
Fenomena FOMO di Era Digital
Media sosial membuat FOMO tumbuh subur. Setiap kali membuka Instagram atau TikTok, kamu disuguhi kehidupan orang lain yang tampak lebih seru dan sukses. Tanpa sadar, kamu mulai membandingkan hidupmu dengan “versi editan” milik orang lain.
Contohnya, seseorang bisa merasa gagal hanya karena teman-temannya sudah menikah atau memiliki bisnis, padahal setiap orang punya waktu dan jalannya masing-masing. Dunia digital menciptakan ilusi bahwa semua orang sedang “menang”, padahal yang kamu lihat hanyalah potongan momen terbaik mereka.
Penyebab FOMO dan Pandangan Psikologisnya
1. Media Sosial yang Selalu Aktif
Setiap kali membuka Instagram, TikTok, atau X (Twitter), kamu disuguhi potret hidup orang lain yang tampak sempurna seperti liburan mewah, karier gemilang, hubungan romantis yang bahagia.
Tanpa sadar, kamu mulai membandingkan hidupmu dengan apa yang kamu lihat di layar. Padahal, sebagian besar hanya potongan terbaik dari kehidupan seseorang, hasil kurasi, bukan realita utuh.
Secara psikologis, menurut penelitian dari American Psychological Association, otak manusia cenderung fokus pada kekurangan diri dibanding kelebihan saat membandingkan diri dengan orang lain.
Hal inilah yang memicu rasa tidak cukup, iri, hingga kecemasan sosial yang dikenal sebagai FOMO.
2. Tekanan Sosial dan Tren yang Cepat Berubah
Dunia saat ini bergerak sangat cepat. Setiap minggu ada tren baru, mulai dari gaya berpakaian, tempat nongkrong hits, sampai karier atau investasi yang sedang naik daun. Jika tidak ikut, kamu mungkin merasa tertinggal dan takut tidak dianggap “up to date”.
Dari sisi psikologis, ini berkaitan dengan kebutuhan manusia untuk menjadi bagian dari kelompok (belongingness). Menurut teori Maslow’s Hierarchy of Needs, kebutuhan sosial seperti diterima dan diakui sama pentingnya dengan kebutuhan dasar.
Karena itu, ketika melihat orang lain lebih dulu tahu tren baru, otak menafsirkan situasi itu sebagai ancaman terhadap posisi sosial kita.
3. Rasa Ingin Diterima
Setiap orang ingin diakui dan menjadi bagian dari lingkaran sosialnya. FOMO sering muncul saat seseorang merasa ditinggalkan, misalnya, teman kantor pergi makan siang tanpa mengajaknya, atau grup pertemanan punya agenda tanpa kabar.
Dari sudut pandang psikologi sosial, ini disebut “social exclusion anxiety” yakni kecemasan karena takut tidak diterima. Otak manusia memproses penolakan sosial hampir sama seperti rasa sakit fisik.
Jadi, wajar kalau kamu merasa tidak nyaman saat merasa “tidak diajak”. Namun jika dibiarkan, perasaan ini bisa berkembang menjadi perilaku kompulsif: terus memeriksa pesan, media sosial, atau update teman hanya untuk memastikan kamu tetap terlibat.
4. Kebiasaan Selalu Online
FOMO juga muncul karena kecanduan digital. Notifikasi, pesan baru, dan update teman memberi efek “dopamin hit” kecil di otak, zat kimia yang memicu rasa senang. Lama-kelamaan, otak terbiasa mencari sensasi itu berulang-ulang, membuatmu sulit lepas dari layar.
Psikolog menyebut ini sebagai intermittent reinforcement, yaitu kebiasaan yang terbentuk karena hadiah kecil yang datang tidak menentu. Sama seperti orang yang kecanduan game atau judi, pengguna media sosial juga bisa terus mengejar notifikasi demi rasa “terhubung”, padahal justru makin lelah secara mental.
5. Data yang Menggambarkan Fenomena Ini
Menurut survei GlobalWebIndex, lebih dari 56% pengguna media sosial berusia 16–24 tahun mengaku pernah mengalami FOMO. Angka ini menunjukkan bahwa fenomena ini nyata dan semakin meluas di kalangan muda.
Bahkan, dalam riset Psychiatry Research (2022), disebutkan bahwa tingkat FOMO tinggi berkorelasi dengan peningkatan stres, kecemasan, dan gangguan tidur. Artinya, FOMO bukan sekadar “takut ketinggalan”, tapi sudah menyentuh aspek kesejahteraan mental seseorang.
Tanda-Tanda Kamu Mengalami FOMO
Fenomena FOMO (Fear of Missing Out) kadang muncul tanpa kita sadari. Awalnya hanya sekadar ingin tahu kabar teman atau tren terbaru, tapi lama-lama jadi kebiasaan yang bikin cemas dan sulit fokus.
Kalau kamu mulai merasakan beberapa hal berikut, bisa jadi kamu sedang mengalami FOMO.
1. Selalu Mengecek Media Sosial
Kamu merasa gelisah kalau tidak membuka aplikasi dalam beberapa jam. Notifikasi kecil bisa langsung membuatmu ingin tahu siapa yang posting, siapa yang story, atau siapa yang sedang hangout.
Contoh:
- Baru bangun pagi, hal pertama yang kamu lakukan adalah buka Instagram atau TikTok.
- Setiap lima menit, kamu cek apakah ada like baru di postinganmu.
- Saat kumpul dengan teman, kamu lebih sibuk lihat layar ponsel daripada ngobrol.
- Kalau tidak buka media sosial seharian, kamu merasa “ada yang kurang”.
- Kamu merasa tertinggal kalau tidak tahu topik viral yang sedang dibahas di timeline.
2. Takut Menolak Ajakan
Walau lelah atau sibuk, kamu tetap ikut nongkrong, nonton, atau datang ke acara hanya karena takut tidak diikutsertakan dalam obrolan keesokan harinya.
Contoh:
- Setelah kerja lembur, kamu tetap ikut teman makan malam karena takut dibilang “anti-sosial”.
- Kamu ikut acara komunitas yang tidak kamu minati hanya agar tetap eksis.
- Saat ingin istirahat di rumah, kamu tetap keluar karena takut kehilangan momen.
- Kamu menyesal kalau melihat foto teman hangout tanpa kamu.
- Kamu sering merasa “tertinggal cerita” kalau tidak ikut kumpul.
3. Mudah Membandingkan Diri
Melihat pencapaian orang lain langsung membuatmu merasa tidak cukup—baik dari segi karier, penampilan, atau gaya hidup.
Contoh:
- Teman baru dapat promosi, kamu langsung merasa gagal dengan posisi sekarang.
- Melihat orang lain menikah, kamu jadi mempertanyakan hidupmu sendiri.
- Saat teman liburan ke luar negeri, kamu merasa hidupmu monoton.
- Kamu iri melihat orang lain punya banyak teman atau undangan acara.
- Prestasi orang lain di media sosial terasa seperti pengingat bahwa kamu belum “sampai”.
4. Sulit Fokus
Pikiranmu sering melayang ke hal yang dilakukan orang lain. Bahkan saat sedang mengerjakan sesuatu, kamu merasa perlu mengecek apa yang sedang ramai di luar sana.
Contoh:
- Saat belajar, kamu tiba-tiba membuka TikTok karena “penasaran”.
- Sedang bekerja tapi pikirannya ke “acara siapa yang lagi rame hari ini”.
- Kamu sulit menikmati waktu sendiri tanpa membuka ponsel.
- Notifikasi kecil bisa langsung mengalihkan perhatianmu dari pekerjaan penting.
- Saat nongkrong, kamu sibuk mikir “teman-teman lain lagi di mana, ya?”.
5. Merasa Kehidupanmu Kurang Seru
Kamu sulit menikmati rutinitas sendiri karena merasa hidup orang lain selalu lebih menarik, lebih sibuk, atau lebih bahagia.
Contoh:
- Kamu merasa weekend-mu membosankan karena tidak seaktif orang lain.
- Saat melihat orang lain “healing” ke luar kota, kamu langsung ingin ikut-ikutan.
- Kamu merasa bersalah kalau tidak melakukan hal produktif di hari libur.
- Setiap kali melihat story pesta atau konser, kamu menyesal tidak datang.
- Kamu jarang merasa puas dengan keseharianmu sendiri.
6. Sering Mencari Validasi dari Orang Lain
Kamu merasa berharga hanya ketika postinganmu disukai banyak orang atau saat mendapat pujian di media sosial.
Contoh:
- Kamu hapus foto karena like-nya sedikit.
- Kamu menunggu komentar teman sebagai tanda “dianggap eksis”.
- Kamu sering berpikir keras soal caption agar terlihat keren.
- Kalau tidak ada yang merespons postinganmu, kamu merasa tidak penting.
- Kamu menilai keberhasilan berdasarkan respon orang lain, bukan kepuasan diri.
7. Takut Ketinggalan Tren atau Topik
Kamu merasa perlu selalu tahu apa yang sedang viral agar bisa nyambung dengan orang lain.
Contoh:
- Kamu ikut challenge TikTok hanya karena semua orang melakukannya.
- Kamu menonton film yang sedang ramai dibahas meski sebenarnya tidak tertarik.
- Kamu ganti gaya berpakaian mengikuti influencer yang sedang naik daun.
- Kamu buru-buru beli produk viral walau belum butuh.
- Kamu terus scroll berita terbaru agar tidak ketinggalan gosip atau topik hangat.
8. Cemas Saat Tidak Tersambung Internet
Kehabisan kuota atau sinyal hilang bisa membuatmu panik. Rasanya seperti kehilangan koneksi dengan dunia luar.
Contoh:
- Kamu gelisah saat baterai ponsel hampir habis.
- Saat sinyal lemah, kamu berkali-kali mencoba refresh aplikasi.
- Kamu merasa cemas kalau tidak bisa online seharian.
- Kamu terus mikir “ada apa ya di grup WA” meski sedang tidak penting.
- Kamu sulit menikmati momen tanpa akses internet.
9. Overthinking Setelah Melihat Postingan Orang
Setelah melihat unggahan orang lain, kamu terlalu lama memikirkannya — entah merasa iri, sedih, atau tidak puas dengan hidup sendiri.
Contoh:
- Kamu berpikir “kenapa aku belum seperti dia?”.
- Kamu merasa gagal setiap kali teman pamer pencapaian.
- Kamu menyalahkan diri sendiri karena merasa kurang berusaha.
- Kamu mengulang-ulang postingan seseorang dan menganalisisnya berlebihan.
- Kamu sulit tidur karena memikirkan hal yang kamu lihat di media sosial.
Dampak FOMO terhadap Kesehatan Mental dan Produktivitas
FOMO memang sering dianggap sepele, tapi dampaknya bisa jauh lebih dalam dari sekadar “takut ketinggalan berita”. Jika tidak dikendalikan, FOMO bisa memengaruhi emosi, pola pikir, hingga performa kerja.
Berikut beberapa dampak negatif yang umum terjadi:
1. Menurunnya Rasa Percaya Diri
Terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain membuatmu merasa hidupmu kurang berarti. Kamu mulai meragukan pencapaian sendiri dan merasa tidak cukup, bahkan saat sebenarnya sudah berusaha keras.
Contoh:
Melihat teman seusia sudah punya bisnis sukses membuatmu merasa gagal, meski kamu juga sedang berkembang di jalur berbeda.
2. Munculnya Kecemasan dan Stres Berlebih
FOMO menciptakan tekanan mental untuk selalu “up to date”. Ketika tidak tahu tren baru atau tidak hadir dalam suatu momen, kamu merasa gelisah dan tertinggal.
Contoh:
Kamu merasa cemas setiap kali melihat story teman liburan, atau khawatir kariermu lambat dibanding orang lain.
3. Gangguan Tidur
Kebiasaan scrolling sebelum tidur untuk “cek update terbaru” bisa membuat otak tetap aktif, sulit tenang, dan akhirnya sulit tidur.
Contoh:
Kamu berniat tidur jam 10 malam, tapi terus buka media sosial sampai lewat tengah malam karena takut ada kabar menarik yang terlewat.
4. Kelelahan Emosional (Emotional Burnout)
Terlalu banyak konsumsi informasi sosial membuat mental jenuh. Kamu bisa merasa lelah tanpa sebab jelas karena terus membandingkan hidup sendiri dengan orang lain.
Contoh:
Setiap kali membuka media sosial, kamu merasa “tertekan” melihat orang lain tampak lebih bahagia atau sukses.
5. Penurunan Produktivitas Kerja
FOMO membuat fokusmu mudah teralihkan. Alih-alih menyelesaikan tugas penting, kamu sibuk memantau aktivitas orang lain di internet.
Contoh:
Kamu membuka media sosial di sela kerja “sebentar saja”, tapi akhirnya kehilangan fokus selama berjam-jam.
6. Menurunnya Kepuasan Hidup
FOMO menciptakan persepsi bahwa kebahagiaan orang lain selalu lebih besar. Akibatnya, kamu sulit menikmati hasil kerja atau momen kecil dalam hidupmu sendiri.
Contoh:
Kamu merasa weekend-mu membosankan hanya karena teman-temanmu terlihat lebih “seru” di story mereka.
7. Hubungan Sosial yang Tidak Sehat
Ironisnya, terlalu fokus pada kehidupan sosial digital justru bisa menjauhkanmu dari hubungan nyata di dunia nyata. Kamu mungkin hadir secara fisik, tapi pikiranmu sibuk di dunia maya.
Contoh:
Saat nongkrong dengan teman, kamu malah sibuk scrolling akun lain dan melewatkan momen bersama.
8. Meningkatnya Impulsifitas dan Konsumtifitas
FOMO sering membuat seseorang mengambil keputusan tergesa-gesa seperti membeli barang, ikut acara, atau mengikuti tren tanpa pertimbangan matang.
Contoh:
Kamu membeli tiket konser atau gadget terbaru hanya karena semua orang posting, bukan karena benar-benar butuh.
9. Gangguan Konsentrasi dan Fokus
Karena otak terus mencari rangsangan baru, kamu sulit fokus dalam waktu lama. Perhatianmu terbagi antara pekerjaan dan keinginan untuk terus “update”.
Contoh:
Kamu membaca laporan kerja, tapi setiap notifikasi muncul langsung menghentikan aktivitasmu.
10. Potensi Depresi Jangka Panjang
Dalam kasus ekstrem, FOMO yang kronis bisa menyebabkan rasa tidak puas mendalam dan perasaan “tidak pernah cukup”. Jika dibiarkan, hal ini bisa berkembang menjadi depresi ringan hingga berat.
Contoh:
Kamu merasa hidupmu tidak sebermakna milik orang lain, kehilangan semangat, dan sering merasa hampa tanpa alasan jelas.
Cara Mengatasi FOMO
Agar produktivitas tidak menurun gara-gara FOMO, Grameds bisa melakukan hal di bawah ini:
1. Batasi Waktu di Media Sosial
Gunakan fitur screen time agar tahu seberapa lama kamu online setiap hari. Coba kurangi secara bertahap.
2. Sadari bahwa Media Sosial Hanya Highlight
Apa yang kamu lihat hanyalah potongan terbaik hidup orang lain, bukan keseluruhan cerita.
3. Nikmati Momen Saat Ini (Mindfulness)
Fokus pada aktivitas yang sedang kamu jalani. Latih diri untuk benar-benar hadir di momen tersebut.
4. Tentukan Prioritas Hidupmu Sendiri
Tidak semua tren harus diikuti. Tentukan apa yang benar-benar penting dan relevan untuk dirimu.
5. Bangun Hubungan Nyata
Gantilah waktu scrolling dengan ngobrol langsung bersama keluarga atau teman. Interaksi nyata lebih menenangkan daripada validasi digital.
Dengan kebiasaan sederhana ini, kamu bisa perlahan mengendalikan dorongan FOMO dan lebih menikmati hidup.
Kenali JOMO: Joy of Missing Out
Kalau FOMO adalah takut tertinggal, JOMO (Joy of Missing Out) adalah kebalikannya, yakni menikmati ketenangan karena tidak ikut dalam semua hal.
JOMO mengajarkan bahwa tidak apa-apa untuk offline, tidak mengikuti semua tren, atau menolak ajakan yang tidak sesuai dengan prioritasmu. Dengan JOMO, kamu belajar menghargai waktu sendiri, menikmati kesunyian, dan hidup tanpa tekanan sosial.
Contoh aktivitas JOMO yaitu membaca buku tanpa gangguan, berolahraga ringan, menulis jurnal, atau sekadar menikmati kopi tanpa membuka ponsel.
Menariknya, banyak ahli psikologi sepakat bahwa menerapkan JOMO bisa menurunkan stres hingga 30% karena otak mendapat waktu istirahat dari arus informasi digital yang berlebihan.
Kesimpulan: Hidup Tanpa FOMO Itu Mungkin
Grameds, FOMO adalah fenomena umum di era digital, tapi bukan berarti kamu harus terjebak di dalamnya. Dengan kesadaran diri, manajemen waktu online yang baik, dan keberanian untuk berkata “tidak”, kamu bisa menemukan keseimbangan baru dalam hidup.
Ingat, kebahagiaan tidak diukur dari seberapa banyak hal yang kamu ikuti, tapi seberapa tenang kamu menjalani hidupmu sendiri.
Kalau Grameds ingin belajar lebih dalam tentang kesehatan mental, mindfulness, dan keseimbangan hidup, temukan buku-buku inspirasinya di Gramedia.com
- Novel Fantasi
- Novel Best Seller
- Novel Romantis
- Novel Fiksi
- Novel Non Fiksi
- Rekomendasi Novel Terbaik
- Rekomendasi Novel Horor
- Rekomendasi Novel Remaja Terbaik
- Rekomendasi Novel Fantasi
- Rekomendasi Novel Fiksi
- Rekomendasi Buku Tentang Insecure
- Rekomendasi Buku Motivasi Kerja
- Rekomendasi Buku Shio
- Rekomendasi Buku Tentang Kehidupan
- Rekomendasi Buku TOEFL
- Rekomendasi Buku Menambah Wawasan
- Rekomendasi Novel Motivasi
- Ascribed Status
- Arti FOMO
- Arti Worth It Banget
- Arti Yapping
- Ballerina Cappucino
- Contoh Perubahan yang Direncanakan
- For You Page
- Gong Xi Fa Cai
- Jikoshoukai
- Kelompok Informal
- Offshore
- Overrated dan Underrated
- Safety Induction
- Sasageyo
- Shibal Sekiya
- Tektok Adalah
- Tirakat Adalah
- Tongue Twister
- Undergraduate Adalah
- Vibes
- YOLO