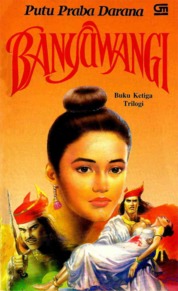Mengenal Asal-Usul dan Adat-Istiadat 5 Suku Terbesar di Jawa – Indonesia merupakan salah satu negeri yang kaya raya. Kekayaan itu tidak sebatas mengacu dari hasil alamnya saja, tetapi juga ragam suku, bahasa, agama, kepercayaan, dan adat istiadat. Untuk kekayaan suku bangsa, Indonesia memiliki ratusan nama suku, bahkan ribuan jika dirinci hingga subsukunya.
Setiap suku memiliki adat dan norma yang berbeda-beda. Pun demikian, keberagaman tersebut tidak membuat keutuhan bangsa terpecah-pecah. Sebaliknya, keberagaman menyatu untuk mencapai tujuan masyarakat yang adil dan makmur.
Data suku di Indonesia sendiri pertama kali dihasilkan melalui Sensus Penduduk (SP) 1930 oleh pemerintah kolonial Belanda. Namun, pengumpulan data ini sempat terhenti pada masa Orde Baru disebabkan adanya political taboo yang memandang bahwa pembahasan suku adalah upaya yang dapat mengancam keutuhan bangsa. Barulah 70 tahun kemudian, data suku tersebut mulai dikumpulkan kembali pada masa Reformasi oleh BPS melalui SP2000, yang dilanjutkan dengan SP2010.
Setidaknya, ada sekitar 1.340 suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Catatan yang dihimpun oleh BPS tahun 2010 menyebutkan bahwa suku Jawa merupakan suku terbesar dengan proporsi 40,05% dari jumlah penduduk di Indonesia. Sisanya adalah suku-suku yang mendiami wilayah di luar Jawa, seperti suku Bugis (3,68%), Batak (2,04%), Bali (1,88%), Aceh (1,4%), dan suku-suku lainnya.
Masyarakat Jawa di sisi lain tidak hanya mendiami Pulau Jawa saja, tetapi ada juga yang berada di luar Pulau Jawa dengan tetap mempertahankan nilai-nilai budayanya. Oleh karena itu, kebudayaan Jawa dinilai besar dan sangat beragam dari berbagai sisi.
Mayoritas masyarakat Jawa beragama Islam, meskipun saat ini sudah banyak yang menganut agama-agama lain. Adapun perekonomian utama masyarakatnya berasal dari bidang pertanian. Masyarakat perdesaan banyak yang bekerja sebagai petani dan menggarap sawah. Selain itu, mereka juga banyak yang mengerjakan usaha sebagai perajin, misalnya mencetak batu bata, membatik, mengayam, hingga menjadi tukang kayu. Sementara itu, masyarakat Jawa yang tinggal di daerah pesisir umumnya bekerja sebagai nelayan dan menjualnya di tempat pelelangan ikan.
Secara umum, wilayah Jawa mayoritas didiami oleh suku Jawa, yang terbagi ke dalam beberapa suku atau subsuku. Selain suku Jawa, suku-suku besar lain yang mendiami wilayah ini adalah suku Samin, Tengger, Osing, dan Bawean.
Agar lebih memahami asal-usul dan adat istiadat suku-suku tersebut, mari kita simak bersama-sama gambaran dan penjelasan berikut.
Daftar Isi
1. Suku Jawa

Masyarakat Jawa mengadaptasi banyak aspek budaya India, seperti wiracarita Ramayana.
(Foto: Gunawan Kartapranata)
Suku Jawa merupakan suku bangsa terbesar di Indonesia yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Indramayu, Kabupaten/Kota Cirebon (Jawa Barat), dan Kabupaten/Kota Serang–Cilegon (Banten). Pada 2010, setidaknya 40,22% penduduk Indonesia merupakan etnis Jawa. Selain itu, suku Jawa ada pula yang berada di negara Kaledonia Baru dan Suriname, karena pada masa kolonial Belanda suku ini dibawa ke sana sebagai pekerja.
Saat ini, suku Jawa di Suriname menjadi salah satu suku terbesar di sana dan dikenal sebagai Jawa Suriname. Ada juga sejumlah besar suku Jawa di sebagian besar provinsi di Indonesia, Malaysia, Singapura, Arab Saudi, dan Belanda.
Mayoritas suku Jawa adalah penganut agama Islam, dengan beberapa minoritas Kristen, Kejawen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pun demikian, peradaban orang Jawa telah dipengaruhi interaksi antara budaya Kejawen dan Hindu-Buddha selama lebih dari seribu tahun. Pengaruh ini masih terlihat dalam sejarah, budaya, tradisi, dan bentuk kesenian Jawa.
Masyarakat Jawa masih memegang teguh kepercayaan Kejawen. Kejawen sendiri merupakan ajaran yang dianut oleh para filsuf Jawa dan menjadi ajaran utama dalam membangun tata krama atau aturan dalam berkehidupan yang lebih baik. Kejawen merupakan suatu kepercayaan, bukan sebuah agama. Kejawen lebih berupa seni, budaya, tradisi, sikap, ritual, dan filosofi masyarakat Jawa yang tidak terlepas dari spiritualitas suku Jawa.
Aliran Kejawen ini kemudian berkembang seiring dengan agama yang dianut oleh pengikutnya, sehingga kemudian dikenal sebagai Islam Kejawen, Hindu Kejawen, Buddha Kejawen, dan Kristen Kejawen. Saat ini, kepercayaan Kejawen dianggap kuno bagi sebagian orang. Namun, masih banyak masyarakat yang menjalankan tradisi, upacara, dan ritual Kejawen seperti nyadran, mitoni, tedhak siten, wetonan, dan lain-lain.
Secara tradisional, mayoritas orang Jawa berprofesi sebagai petani. Pertanian sangat umum karena daerah Jawa memilki tanah vulkanik yang subur. Adapun komoditas pertanian utamanya adalah beras. Pada ahun 1997, diperkirakan bahwa Jawa menghasilkan 55% dari total hasil panen Indonesia. Sebagian besar petani bekerja di sawah skala kecil, dengan persentase 42% di antaranya bekerja dan mengolah langsung tanpa mempekerjakan orang lain.
2. Suku Samin

Suku Samin di Blora.
Suku Samin adalah sekelompok masyarakat yang menganut ajaran Saminisme. Ajaran ini berasal dari seorang tokoh bernama Samin Surosentiko yang lahir pada tahun 1859 di Desa Ploso Kedhiren, Klopodhuwur, Randublatung, Blora. Ajaran tersebut muncul sebagai reaksi terhadap pemerintah kolonial Belanda yang sewenang-wenang terhadap orang-orang pribumi.
Perlawanan mereka dilakukan tidak hanya secara fisik, tetapi juga berwujud pertentangan terhadap segala peraturan dan kewajiban yang harus dilakukan rakyat terhadap pemerintahan kolonial Belanda saat itu, termasuk menolak membayar pajak.
Masyarakat Samin memiliki kepribadian yang polos dan jujur. Artinya, mereka terbuka kepada siapa pun, termasuk kepada orang-orang yang belum dikenalnya. Mereka menganggap semua orang sebagai saudara, sehingga selalu mengutamakan sikap kebersamaan. Segala sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat tidak pernah direkayasa. Hal ini dikarenakan jujur merupakan satu dari sekian wujud sifat masyarakat Samin dari ajaran yang dianutnya.
Masyarakat Samin sangat memegang “solat” yang berarti solahing ilat (gerak lidah). Lidah harus dijaga agar tetap mengucapkan kata-kata yang jujur dan tidak pernah menyakiti orang lain. Lidah adalah sumber dari segala masalah. Jangan menyakiti orang lain kalau tidak mau disakiti, jangan membohongi orang lain kalau tidak mau dibohongi, dan jangan mencelakai orang lain kalau tidak mau dicelakai.
Masyarakat Samin umumnya berkomunikasi menggunakan bahasa Jawa lugu atau Jawa ngoko alus yang kadang bercampur bahasa krama. Oleh karena itu, pembicaraan mereka terdengar agak kasar seperti layaknya karakter orang Jawa Timuran.
Masyarakat Samin mengejawantahkan kehidupan dengan solidaritas sosial. Saat ini, masyarakat Samin menggunakan kiat atau strategi yang disebut ngumumi, yaitu diam dan tidak melawan pemerintah, tetapi tetap mengkritisi secara pasif. Pendeknya, dalam hidup masyarakat Samin tidak pernah menolak segala bentuk bantuan dari pemerintah, tetapi mereka juga tidak pernah meminta bantuan kepada siapa pun.
Hadirnya teknologi baru diakui telah membantu mereka untuk mendapatkan pengalaman, terutama dalam pembangunan pertanian maupun program-program pembangunan lainnya. Masyarakat Samin kini sedang mengalami transisi menuju masyarakat modern, yang terwujud dalam bentuk interaksi asosiatif dan disosiatif.
Kesan masyarakat Samin memang selalu diidentikkan dengan keterisolasian dan keterbelakangan. Namun, hadirnya piranti elektronik modern, seperti radio, televisi, gawai, mesin cuci, sepeda motor, traktor, mesin penggiling padi, saat ini telah menjadi bagian dari hidup keseharian mereka.
Masyarakat Samin bahkan ada yang telah mengenyam pendidikan hingga S2 dan berprofesi menjadi PNS, polisi, petugas kesehatan, bidan, dan sebagainya. Hal menarik dari sikap masyarakat Samin saat ini adalah keteguhan terhadap ajarannya, meskipun telah “membuka diri” dengan dunia luar. Mereka tetap berpedoman kepada ajaran Saminis, yaitu tetap menjunjung tinggi kejujuran, toleransi, kebersamaan, dan kegotongroyongan.
3. Suku Tengger

Upacara Melasti yang dilakukan oleh suku Tengger di Bromo.
Suku Tengger atau sering juga disebut dengan wong Brama adalah suku yang mendiami dataran tinggi di sekitar kawasan Pegunungan Bromo–Tengger–Semeru, Provinsi Jawa Timur. Penduduk suku ini menempati sebagian wilayah Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Malang.
Kondisi lingkungan suku Tengger yang tinggal di kaki gunung memengaruhi kepercayaan penduduknya terhadap makna sebuah gunung. Bagi suku Tengger, Gunung Bromo (masyarakat setempat menyebutnya Gunung Brahma) dipercaya sebagai gunung yang suci. Mereka mempercayai bahwa nenek moyang mereka berada di dalam Gunung Bromo tersebut, sehingga banyak dari upacara yang mereka lakukan adalah bagian dari pemujaan nenek moyang yang dilakukan di kaki Gunung Bromo.
Ada banyak makna yang dikandung dari kata “tengger”. Secara etimologis, tengger berarti berdiri tegak serta diam tanpa bergerak (bahasa Jawa: anteng). Jika dikaitkan dengan adat dan kepercayaan, arti “tengger” adalah tengering budi luhur (tanda bahwa warganya memiliki budi luhur).
Menurut legenda, asal usul suku Tengger erat kaitannya dengan cerita mengenai Rara Ateng dan Jaka Seger. Nama Tengger sendiri diambil dari nama keduanya, yakni -teng dari akhiran nama Rara Anteng dan -ger dari akhiran nama Jaka Seger. Masyarakat suku Tengger memercayai bahwa mereka adalah keturunan dari keduanya.
Legenda tersebut menceritakan bahwa sepasang suami-istri ini sudah sewindu usia pernikahan belum juga dikaruniai anak. Mereka bertapa selama enam tahun dan setiap tahunnya berganti arah. Sang Hyang Widi Wasa lantas menanggapi semedi mereka.
Dari puncak Gunung Bromo kemudian keluar semburan cahaya yang menyusup ke dalam jiwa Rara Ateng dan Jaka Seger. Ada pawisik (bisikan) yang mengatakan jika mereka akan dikaruniai anak, tetapi anak terakhir harus dikorbankan di kawah Gunung Bromo.
4. Suku Osing

Tiga generasi perempuan suku Osing di Banyuwangi tahun 1910-an.
(Foto:Tropenmuseum)
Suku Osing adalah penduduk asli Banyuwangi yang juga disebut sebagai Laros (akronim dari Lare Osing) atau Wong Blambangan. Mereka menggunakan bahasa Osing, yang masih termasuk subdialek bahasa Jawa bagian timur dan berkerabat dengan bahasa Jawa Arekan dan bahasa Tengger.
Suku ini menempati beberapa kecamatan di Kabupaten Banyuwangi bagian tengah dan bagian timur. Mayoritas berada di Kecamatan Songgon, Kecamatan Rogojampi, Kecamatan Blimbingsari, Kecamatan Singojuruh, Kecamatan Kabat, Kecamatan Licin, Kecamatan Giri, Kecamatan Glagah, dan sebagian berada di Kecamatan Banyuwangi, Kecamatan Kalipuro dan Kecamatan Sempu yang berbaur dengan komunitas suku Madura dan Bali.
Kesenian utama dari suku tersebut, yaitu Gandrung Banyuwangi, Patrol, Seblang, Angklung, Tari Barong, Kuntulan, Kendang Kempul, Janger, Jaranan, Jaran Kincak, Angklung Caruk, dan Jedor.
5. Suku Bawean

Sekelompok orang Bawean di Singapura tahun 1901.
(Foto: National Archives of Singapore)
Suku Bawean juga dikenal dengan nama Boyan atau Bhebien. Suku ini terbentuk karena terjadinya percampuran antara orang Madura, Melayu, Jawa, Banjar, Bugis, dan Makassar selama ratusan tahun di pulau Bawean. Masyarakat Melayu Malaka dan Malaysia lebih mengenal suku tersebut dengan sebutan Boyan daripada Bawean. Menurut pandangan mereka, boyan berarti “sopir” dan “tukang kebun” (kepbhun dalam bahasa Bawean), sesuai dengan mata pencaharian sebagian masyarakat asal Bawean.
Orang-orang Bawean merupakan satu kelompok kecil dari masyarakat Jawa yang berasal dari Pulau Bawean. Pulau ini terletak di Laut Jawa, yaitu di antara Pulau Kalimantan di sebelah utara dan Pulau Jawa di sebelah selatan. Pulau tersebut terletak sekitar 80 mil ke arah utara Surabaya dan masuk kabupaten Gresik. Pulau itu terdiri atas dua kecamatan, yaitu Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak.
Menurut penelitian bersama yang dilakukan oleh Muhammad Ihwanus Sholik dan para peneliti lain (2016) dalam jurnal berjudul Merantau Sebagai Budaya (Eksplorasi Sistem Sosial Masyarakat Pulau Bawean), masyarakat Bawean merantau untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Penduduk suku ini disebut sering bepergian ke berbagai daerah untuk mencari pekerjaan. Mereka sering melakukan perantauan ke berbagai daerah di Indonesia dan luar negeri seperti Singapura dan Malaysia.
Keinginan merantau yang ada dalam suku ini sudah ditanamkan sedari kecil. Kebiasaan ini seperti sudah menjadi budaya yang tidak terpisahkan dari kehidupan suku Bawean. Tarmizi (2017) dalam Tradisi Maulud Masyarakat Suku Bawean di Kampung Sungai Datuk, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan turut menambahkan jika budaya merantau ini sudah melekat dalam diri seorang laki-laki dari suku Bawean sejak abad ke-19.
Kedatangan suku ini ke Melaka sangatlah sulit dipastikan karena tidak ada bukti dan dokumentasi sejarah yang kuat. Berbagai pendapat yang dikemukakan tidak dapat menunjukkan ketepatan waktu. Pendapat pertama mengatakan bahwa ada orang yang bernama Tok Ayar datang ke Malaka pada 1819. Pendapat kedua mengatakan bahwa orang Bawean datang pada 1824, kira-kira ketika Inggris melakukan penjajahan di Malaka.
Berdasarkan catatan Pemerintah Koloni Singapura tahun 1849, setidaknya terdapat 763 orang Bawean di Malaka dan jumlah itu terus bertambah, sedangkan Persatuan Bawean Malaysia mencatat terdapat 3.161 orang Bawean yang tersebar di Kuala Lumpur, Johor Bahru, Melaka, Seremban, dan Ipoh pada 1891.
Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa orang Bawean sudah ada di Melaka sebelum tahun 1900 dan saat itu sudah banyak orang Bawean di Melaka. Masyarakat Bawean umumnya tinggal di kota atau daerah yang dekat dengan kota, seperti di Kampung Mata Kuching, Klebang Besar, Limbongan, Tengkera, dan kawasan sekitar Rumah Sakit Umum Melaka. Jarang ditemui orang Bawean yang tinggal di kawasan-kawasan yang jauh dari kota dan jumlah mereka di Melaka diperkirakan tidak melebihi seribu orang.
Selain di Melaka, orang Bawean juga tersebar di Lembah Klang, seperti di kawasan Ampang, Gombak, Balakong, dan Shah Alam. Mereka membeli tanah dan membangun rumah secara berkelompok. Sekurang-kurangnya, ada dua keluarga besar masyarakat Bawean di Gelugor, Pulau Pinang. Mereka menggunakan bahasa Melayu dialek Pulau Pinang untuk bertutur dengan masyarakat yang bukan berasal dari Bawean.
Nah, itulah penjelasan singkat mengenai Asal-Usul dan Adat-Istiadat 5 Suku Terbesar di Jawa. Berikut ini rekomendasi buku dari Gramedia yang bisa Grameds baca untuk mempelajari tentang suku-suku di Indonesia agar bisa memahaminya secara penuh. Selamat membaca.
Temukan hal menarik lainnya di www.gramedia.com. Gramedia sebagai #SahabatTanpaBatas akan selalu menampilkan artikel menarik dan rekomendasi buku-buku terbaik untuk para Grameds.
Penulis: Fandy Aprianto Rohman
BACA JUGA:
- 4 Teori Asal Usul Nenek Moyang Bangsa Indonesia Terlengkap
- Daftar Suku Bangsa di Indonesia serta Pranata Sosial Masyarakatnya
- Pakaian Adat Papua: Jenis, Keunikan, dan Filosofinya
- Rumah Adat di Indonesia yang Unik dan Jarang Diketahui
- Rumah Adat Maluku: Nama, Sejarah, Jenis, Keunikan, dan Gambar
- Rumah Adat Papua: Jenis, Fungsi, Keunikan, dan Filosofi