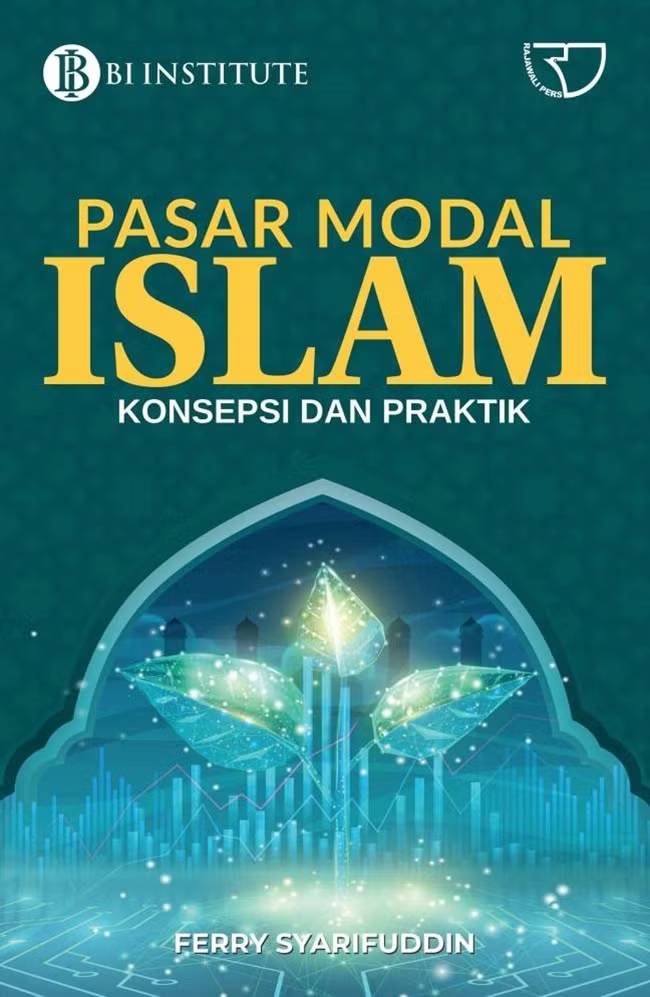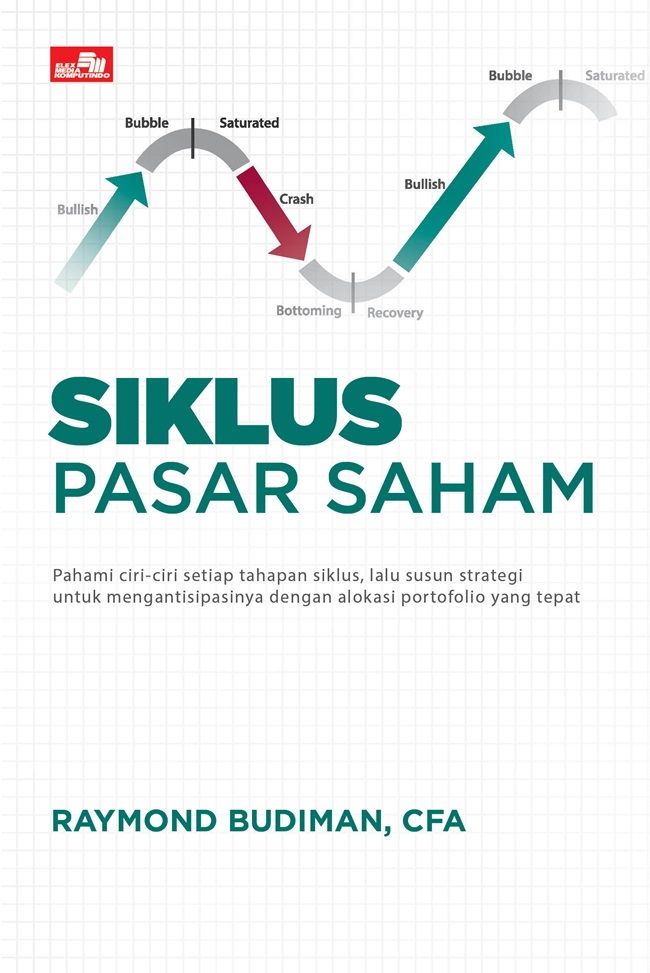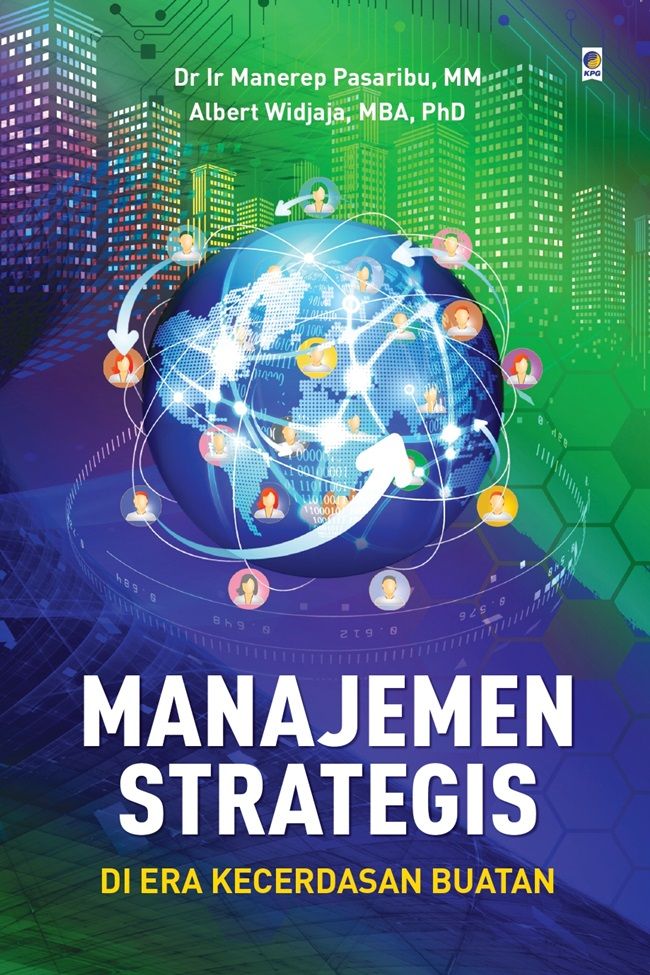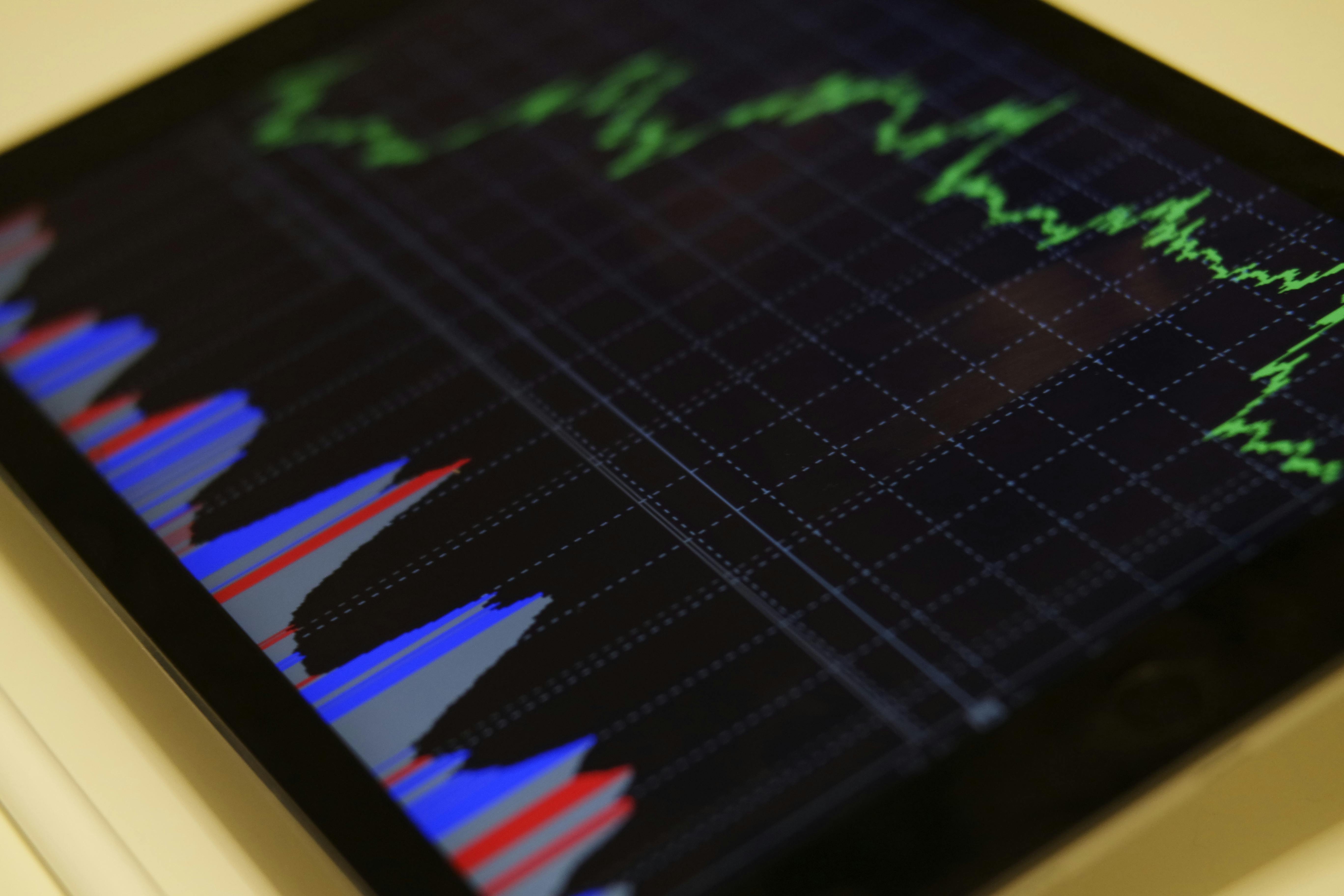contoh pasar monopsoni – Halo Grameds! Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti sering berinteraksi dengan pasar, entah saat belanja kebutuhan pokok, membeli pulsa, atau menjual hasil panen bagi yang tinggal di desa.
Pasar bukan hanya soal tempat jual beli, tapi juga sistem yang mengatur bagaimana harga terbentuk dan siapa yang punya kuasa dalam menentukan nilai suatu barang atau jasa. Nah, salah satu bentuk pasar yang jarang dibahas tapi sebenarnya cukup dekat dengan kehidupan banyak orang adalah pasar monopsoni.
Pasar monopsoni yaitu kondisi ketika hanya ada satu pembeli tapi banyak penjual. Lewat artikel ini, kita akan bahas tuntas seperti apa bentuk pasar monopsoni itu, dan contoh nyatanya dalam berbagai sektor yang mungkin selama ini tidak kita sadari.
Daftar Isi
Pengertian Pasar Monopsoni
Pasar monopsoni adalah struktur pasar di mana hanya ada satu pembeli utama, sementara penjualnya banyak. Dalam sistem ini, pembeli memiliki kekuatan penuh untuk menentukan harga dan syarat transaksi, karena penjual tidak punya alternatif lain. Istilah “monopsoni” berasal dari bahasa Yunani monos (satu) dan opsōnion (pembeli barang dagangan).
Pasar monopsoni itu, sederhananya, adalah kondisi ketika hanya ada satu pihak yang membeli, sedangkan penjualnya banyak dan tersebar. Jadi bayangkan begini: kamu dan teman-temanmu adalah petani yang punya hasil panen, tapi di wilayahmu cuma ada satu pabrik atau pembeli besar yang bersedia membeli produk itu.
Karena cuma ada satu pembeli, pihak itulah yang pegang kendali. Dia bisa menentukan berapa harga beli, kapan transaksi dilakukan, dan bahkan kualitas seperti apa yang mereka mau. Mau tidak mau, kamu harus ikut aturan main mereka. Jika tidak demikian, nanti hasil panenmu bisa tidak laku.
Nah, dalam istilah ekonomi, ini sering disebut pasar input, karena yang diperjualbelikan biasanya adalah faktor produksi seperti tenaga kerja, bahan mentah, atau hasil pertanian.
Misalnya, seorang guru honorer hanya bisa bekerja di sekolah negeri milik pemerintah; berarti pemerintah jadi pembeli tunggal jasa tenaga pengajar. Di sini, posisi guru sebagai penjual jasa tidak punya banyak pilihan lain.
Bedanya dengan pasar biasa, dalam monopsoni pembeli lah yang paling kuat. Jadi kalau dalam pasar monopoli penjual bisa semena-mena menentukan harga karena tak punya saingan, di monopsoni justru pembelinya yang bisa menekan harga karena dia satu-satunya tujuan para penjual.
Makanya, memahami struktur seperti ini penting banget, apalagi kalau kita bicara soal keadilan ekonomi dan keseimbangan dalam transaksi.
Contoh Nyata Pasar Monopsoni

Sumber: Pexels
Agar kamu lebih mudah memahami bagaimana pasar monopsoni terjadi di dunia nyata, berikut ini adalah beberapa contoh konkret yang sering terjadi di berbagai sektor. Setiap contoh menunjukkan bagaimana satu pembeli besar bisa menguasai pasar, sementara banyak penjual bergantung padanya.
1. Pemerintah sebagai Pembeli Tenaga Kerja ASN (Guru, TNI, Polisi)
Di sektor ketenagakerjaan, contohnya bisa kamu lihat pada profesi guru negeri, tentara, atau polisi. Mereka menjual jasa atau tenaga kerja, tapi satu-satunya pembeli adalah pemerintah. Karena tidak ada instansi lain yang bisa membeli jasa mereka dalam kapasitas resmi, pemerintah jadi pemegang kuasa dalam menentukan gaji, tunjangan, dan kebijakan kerja. Ini adalah bentuk monopsoni dalam pasar tenaga kerja.
2. Petani Tebu dan Pabrik Gula di Daerah Tertentu
Di beberapa daerah penghasil tebu, seperti Jawa Timur atau Lampung, petani sering hanya bisa menjual hasil panennya ke satu pabrik gula terdekat. Mereka tidak punya opsi lain karena keterbatasan transportasi, akses ke pasar luar, atau kontrak kemitraan. Pabrik gula inilah yang kemudian memegang kendali atas harga beli dan waktu panen, yang membuat posisi tawar petani sangat lemah.
3. Nelayan Tradisional dan Pengepul Besar (Eksportir)
Nelayan kecil di daerah pesisir seperti Maluku atau Nusa Tenggara sering hanya memiliki satu pembeli besar, yaitu pengepul atau eksportir ikan laut. Karena hanya pihak itu yang mampu membeli dalam jumlah besar dan menyalurkan ke luar daerah, nelayan pun terpaksa menerima harga yang ditawarkan meski kadang tidak sesuai dengan harga pasar. Ini adalah contoh nyata pasar monopsoni di sektor kelautan.
4. Petani Sawit Rakyat dan Pabrik Kelapa Sawit (CPO Mill)
Di sektor perkebunan, petani sawit rakyat sering terikat untuk menjual buah sawit mereka ke satu pabrik pengolahan (CPO mill) di wilayah mereka. Karena tidak ada pesaing lain dan buah sawit harus segera diproses setelah dipanen, petani tak punya pilihan selain mengikuti harga yang ditetapkan oleh pabrik. Situasi ini memperlihatkan bagaimana satu pembeli bisa mengontrol pasar input di tingkat lokal.
5. Perusahaan Besar Pembeli Karet di Pedalaman Sumatra/Kalimantan
Beberapa perusahaan multinasional membeli bahan mentah karet dari desa-desa penghasil karet alam. Karena hanya ada satu perusahaan yang membeli dalam skala besar, para penyadap karet terpaksa bergantung pada harga dan sistem pembayaran yang ditentukan oleh perusahaan tersebut. Monopsoni semacam ini bisa menimbulkan ketergantungan ekonomi jangka panjang.
Ciri-Ciri Pasar Monopsoni

Sumber: Pexels
Meskipun bentuk pasarnya tidak selalu terlihat langsung, struktur seperti ini bisa ditemukan di banyak sektor, terutama di daerah-daerah tertentu. Yuk simak penjelasannya satu per satu.
1. Hanya Ada Satu Pembeli
Ciri paling mendasar dari pasar monopsoni adalah keberadaan satu pembeli dominan di pasar. Artinya, semua penjual hanya memiliki satu tujuan untuk menjual barang atau jasanya. Karena tidak ada pesaing lain sebagai pembeli, pihak ini otomatis memegang kendali terhadap seluruh transaksi. Misalnya, dalam sektor pendidikan formal negeri, pemerintah adalah satu-satunya pembeli jasa tenaga kerja guru ASN.
2. Banyak Penjual atau Pemasok
Di sisi lain, jumlah penjual atau pemasok barang/jasa cenderung banyak dan terpisah-pisah. Mereka tidak terorganisasi dan biasanya memiliki posisi tawar yang lemah karena bergantung pada satu pembeli. Contohnya bisa kita lihat pada petani kecil yang menjual hasil panen ke satu-satunya pabrik pengolah di daerahnya. Dalam kondisi seperti ini, penjual tidak punya banyak pilihan.
3. Pembeli Bisa Menentukan Harga
Karena tidak ada saingan, pembeli memiliki kekuasaan besar dalam menentukan harga beli. Bahkan, harga bisa ditetapkan lebih rendah dari harga ideal pasar karena penjual tak punya opsi untuk menawar. Ini membuat pendapatan penjual bisa sangat bergantung pada kebijakan si pembeli. Di sinilah muncul ketimpangan yang sering jadi sorotan dalam pasar monopsoni.
4. Penjual Sulit Pindah ke Pasar Lain
Dalam pasar monopsoni, mobilitas penjual sangat terbatas. Baik karena faktor geografis, akses informasi, ataupun tidak adanya pembeli alternatif. Seorang petani, misalnya, tak bisa begitu saja menjual hasil panennya ke kota lain karena keterbatasan biaya, fasilitas distribusi, atau perjanjian kontrak.
5. Transaksi Bergantung pada Ketentuan Pembeli
Ciri lainnya, hampir seluruh aturan main dalam transaksi ditentukan oleh pembeli. Mulai dari waktu pembelian, kualitas produk yang diterima, hingga sistem pembayaran. Penjual hanya bisa mengikuti atau tidak mendapat pemasukan sama sekali.
Perbedaan Pasar Monopoli dan Monopsoni
Apakah Grameds suka keliru antara pasar monopsoni dan monopoli? Pasar monopsoni dan pasar monopoli memang terdengar mirip, tapi sebenarnya keduanya berada di sisi yang berlawanan dalam sistem ekonomi. Pasar monopoli terjadi ketika hanya ada satu penjual yang menguasai seluruh pasar, sementara pembelinya banyak. Artinya, si penjual bisa menentukan harga dan kuantitas barang sesuai kehendaknya karena tidak punya pesaing.
Contoh paling sederhana adalah ketika perusahaan listrik negara menjadi satu-satunya penyedia listrik, masyarakat sebagai pembeli jadi tidak punya alternatif lain.
Sementara itu, pasar monopsoni adalah kebalikannya, yakni hanya ada satu pembeli, sedangkan penjualnya banyak. Dalam kondisi ini, pembeli punya kekuasaan besar dalam menentukan harga dan syarat pembelian karena para penjual bergantung sepenuhnya padanya.
Contohnya, bisa kamu lihat pada petani kecil yang hanya bisa menjual hasil panennya ke satu pabrik pengolahan di wilayah tersebut.
Jika kita bandingkan, keduanya sama-sama menciptakan ketimpangan kekuasaan dalam transaksi, tetapi arahnya berbeda. Di pasar monopoli, penjual yang mendominasi, sedangkan di pasar monopsoni, pembelilah yang memegang kendali.
Dampaknya pun serupa, yaitu bisa menekan harga, mengurangi pilihan, dan melemahkan daya tawar pihak yang jumlahnya lebih banyak. Maka dari itu, penting bagi kita memahami kedua konsep ini agar bisa mengenali struktur pasar yang tidak seimbang dan mencari solusi untuk memperbaikinya.
| Aspek | Pasar Monopoli | Pasar Monopsoni |
| Pelaku dominan | Satu penjual | Satu pembeli |
| Jumlah lawan transaksi | Banyak pembeli | Banyak penjual |
| Contoh | PLN menjual listrik ke masyarakat | Pemerintah membeli tenaga kerja guru negeri |
| Kekuatan penentu harga | Penjual menentukan harga | Pembeli menentukan harga |
| Fokus pasar | Pasar output (produk jadi) | Pasar input (bahan baku, tenaga kerja, jasa) |
Dampak Positif Pasar Monopsoni

Sumber: Pexels
Meski sering kali dikritik karena menyebabkan ketimpangan dalam pasar, pasar monopsoni juga bisa membawa beberapa dampak positif, terutama jika dikelola dengan bijak. Berikut ini beberapa contohnya dalam bentuk penjelasan utuh:
1. Jaminan Pasar bagi Penjual Kecil
Dalam situasi tertentu, kehadiran satu pembeli besar bisa memberikan kepastian pasar bagi para penjual atau produsen kecil. Misalnya, petani yang bekerja sama dengan pabrik pengolahan atau koperasi besar tidak perlu repot mencari pembeli lain karena hasil panennya sudah pasti akan dibeli. Ini tentu meminimalkan risiko kerugian karena kelebihan stok atau harga pasar yang tidak stabil. Bagi petani yang baru mulai, jaminan semacam ini bisa jadi solusi awal agar usaha mereka tetap hidup.
2. Efisiensi dalam Distribusi dan Pembelian
Karena pembeli hanya satu dan penjualnya banyak, proses pembelian bisa berlangsung lebih efisien dan terpusat. Contohnya, pemerintah sebagai pembeli tunggal alat kesehatan untuk rumah sakit negeri bisa melakukan pengadaan besar-besaran dengan sistem yang lebih terkontrol. Ini membantu menghemat biaya logistik, waktu transaksi, dan koordinasi. Dalam skala nasional, monopsoni semacam ini bisa membantu mempercepat distribusi barang di sektor publik.
3. Standarisasi Produk dan Kualitas
Pembeli tunggal biasanya punya kekuatan untuk menetapkan standar produk tertentu. Meskipun ini bisa jadi tekanan bagi penjual, di sisi lain, ini juga mendorong penjual meningkatkan kualitas dan efisiensi produksinya. Misalnya, perusahaan eksportir hasil laut hanya menerima ikan dengan ukuran dan kualitas tertentu, sehingga nelayan mulai menerapkan teknik tangkap yang lebih baik. Dalam jangka panjang, standarisasi ini bisa mendorong peningkatan kualitas produk lokal di pasar global.
Dampak Negatif Pasar Monopsoni
Di balik beberapa manfaat yang bisa muncul dari pasar monopsoni, struktur pasar ini juga memiliki beragam dampak negatif yang cukup serius, khususnya bagi para penjual atau produsen kecil. Berikut ini adalah beberapa contohnya yang sering terjadi di lapangan:
1. Harga Produk yang Cenderung Ditekan Rendah
Salah satu dampak paling nyata dari pasar monopsoni adalah kemampuan pembeli untuk menekan harga serendah mungkin. Karena penjual tidak punya pilihan lain, mereka sering terpaksa menerima harga yang tidak mencerminkan biaya produksi atau nilai pasar sebenarnya. Contohnya, petani karet atau sawit di pedalaman hanya bisa menjual ke satu pabrik, sehingga harga yang mereka terima bisa sangat rendah, bahkan tidak menutupi ongkos panen dan distribusi.
2. Ketergantungan Ekonomi yang Tinggi
Dalam jangka panjang, pasar monopsoni menciptakan ketergantungan ekstrem terhadap satu pembeli. Jika pembeli tersebut tiba-tiba menghentikan kerja sama atau berpindah lokasi, maka penjual akan kehilangan seluruh akses ke pasar. Ini bisa menyebabkan kebangkrutan, pengangguran, dan krisis ekonomi lokal. Misalnya, ketika satu pabrik pengolahan hasil laut di sebuah desa tutup, para nelayan setempat kehilangan pendapatan karena tak ada lagi pihak yang membeli hasil tangkapan mereka.
3. Minimnya Inovasi dan Pilihan Bagi Penjual
Karena hanya ada satu pembeli yang menetapkan standar, penjual tidak terdorong untuk berinovasi atau menawarkan variasi produk. Mereka cenderung hanya memproduksi apa yang diminta pembeli tanpa mengembangkan nilai tambah atau diversifikasi. Hal ini membuat daya saing penjual sangat terbatas. Dalam jangka panjang, ini bisa melemahkan kualitas produksi lokal dan membuat produsen kecil sulit berkembang.
4. Potensi Eksploitasi Tenaga Kerja
Di sektor jasa, pasar monopsoni juga dapat berujung pada eksploitasi tenaga kerja, karena pekerja hanya bisa menjual jasanya kepada satu institusi saja. Misalnya, guru honorer yang hanya bisa bekerja di sekolah negeri dengan gaji rendah, namun tidak bisa berpindah karena terbatasnya lapangan kerja formal. Situasi ini membuat mereka terjebak dalam sistem kerja yang tidak adil tanpa perlindungan yang memadai.
Upaya Mengurangi Ketimpangan dalam Pasar Monopsoni
Ketimpangan dalam pasar monopsoni memang jadi persoalan serius, terutama karena kekuatan transaksi terlalu berat di pihak pembeli. Tapi bukan berarti tak ada solusi. Berikut ini beberapa upaya nyata yang bisa dilakukan untuk mengurangi ketimpangan dalam pasar monopsoni, yang bisa membantu menciptakan sistem pasar yang lebih adil dan berkelanjutan:
1. Penguatan Koperasi dan Organisasi Penjual
Salah satu cara paling efektif adalah dengan membentuk koperasi atau kelompok usaha bersama. Ketika para penjual kecil seperti petani, nelayan, atau pengrajin bergabung dalam satu wadah, posisi tawar mereka otomatis menjadi lebih kuat. Koperasi bisa menjadi perantara yang menegosiasikan harga, mengatur distribusi, bahkan melakukan pengolahan mandiri agar tidak terlalu bergantung pada satu pembeli besar. Contohnya, koperasi petani kopi di beberapa daerah mampu mengekspor produknya sendiri tanpa harus menjual ke tengkulak.
2. Diversifikasi Akses Pasar dan Teknologi
Untuk menghindari ketergantungan pada satu pembeli, para pelaku usaha kecil perlu didorong untuk membuka akses ke pasar yang lebih luas, termasuk melalui digitalisasi. Dengan memanfaatkan platform e-commerce atau jaringan distribusi yang lebih besar, mereka bisa menjangkau pembeli lain di luar wilayahnya. Misalnya, petani bisa menjual hasil panennya langsung ke konsumen akhir lewat aplikasi pertanian, sehingga bisa mendapatkan harga lebih baik dan mengurangi peran perantara tunggal.
3. Regulasi Pemerintah dan Intervensi Harga
Peran pemerintah juga sangat penting untuk melindungi penjual dari eksploitasi harga. Ini bisa dilakukan lewat kebijakan harga minimum, subsidi, atau regulasi perdagangan yang mencegah praktik monopsoni merugikan. Misalnya, pemerintah bisa menetapkan harga dasar untuk gabah atau karet rakyat, agar pabrik tidak membeli di bawah harga wajar. Intervensi semacam ini penting sebagai penyeimbang kekuatan pasar.
4. Edukasi Ekonomi bagi Penjual dan Produsen Kecil
Ketimpangan dalam pasar monopsoni sering juga terjadi karena minimnya pemahaman ekonomi di kalangan penjual kecil. Oleh karena itu, pelatihan tentang manajemen usaha, pembukuan sederhana, dan strategi pemasaran bisa meningkatkan kemandirian mereka. Ketika produsen punya pengetahuan yang cukup, mereka tidak mudah ditekan oleh pembeli dan bisa membuat keputusan yang lebih cerdas secara bisnis.
5. Kemitraan yang Setara dan Berbasis Kontrak
Kemitraan antara pembeli besar dan produsen kecil sebaiknya dibuat dengan sistem kontrak yang adil dan transparan. Dalam banyak kasus, pembeli besar seperti pabrik atau perusahaan ekspor bisa bermitra dengan petani atau nelayan dengan pembagian risiko dan keuntungan yang jelas. Ini akan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan, bukan sepihak.
Grameds, memahami konsep pasar monopsoni membuka mata kita bahwa struktur pasar tidak selalu seimbang dan adil, terutama bagi para pelaku kecil yang berada di posisi tawar yang lemah.
Dalam dunia nyata, bentuk pasar seperti ini sering terjadi, baik di sektor pertanian, perikanan, hingga tenaga kerja. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tidak hanya mengenali ciri dan dampaknya, tetapi juga memahami bagaimana upaya kolektif bisa mengurangi ketimpangan yang terjadi.
Jika Grameds ingin memperdalam wawasan seputar ekonomi, pasar, dan strategi keuangan yang lebih luas, yuk jelajahi koleksi buku-buku ekonomi pilihan di Gramedia.com. Pengetahuan yang kamu gali hari ini bisa jadi bekal untuk membuat keputusan yang lebih bijak di masa depan.
- Barang Setengah Jadi
- Bunga Tunggal
- Contoh Ilmu Ekonomi Deskriptif
- Contoh Mobilitas Sosial Sinking
- Contoh Rencana Anggaran Event
- Contoh Target Penjualan
- Dasar Hukum Asuransi Syariah
- Faktor Pendorong Globalisasi
- Ilmu Ekonomi Deskriptif
- Invisible Hand dalam Teori Ekonomi
- Jenis Kebutuhan dan Contohnya
- Masalah Pokok Ekonomi Klasik
- Merkantilisme
- Pasar Monopsoni
- Perbedaan LRT dan MRT
- Pergeseran Kurva Permintaan
- Rencana Strategis
- Rumus Pendekatan Produksi
- Usaha Peningkatan Hasil Agraris
- Rumus Pertumbuhan Ekonomi